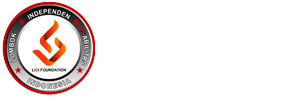Penulis: Lalu Wisnu Pradipta
Pemerhati Disabilitas
Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di berbagai daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), hampir selalu dirayakan dengan gegap gempita. Panggung megah, spanduk keberpihakan, kesaksian pejabat publik, hingga slogan inklusi yang dikumandangkan berulang kali, membentuk sebuah lanskap simbolik bahwa pemerintah hadir untuk difabel. Namun jika dicermati lebih dalam, euforia itu sering kali tidak sejalan dengan implementasi kebijakan jangka panjang yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan inklusif.
NTB, seperti banyak provinsi lain, menghadirkan serangkaian agenda seremonial setiap bulan Desember. Namun panggung kejayaan tidak serta merta mengubah struktur pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara retorika dan kenyataan, atau dalam kajian kebijakan publik disebut sebagai defisit implementasi—kondisi ketika kebijakan berhenti pada tataran komitmen formal, tetapi gagal bertransformasi menjadi tindakan konkret di lapangan.
Sebagai provinsi dengan populasi penyandang disabilitas yang signifikan, NTB sebenarnya telah mengadopsi beberapa regulasi kemajuan: mulai dari Perda Inklusi, pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga pembentukan jejaring penyedia layanan. Namun berbagai instrumen itu sebagian besar masih bersifat normatif, belum terintegrasi dengan sektoral perencanaan dan anggaran.
Fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan disabilitas di NTB masih berada dalam fase awal, yaitu “policy output”, bukan “policy outcome” atau “policy impact”. Artinya, ia telah diproduksi dalam bentuk dokumen, namun belum menghasilkan perubahan struktural. Proses pengarusutamaan disabilitas belum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pembangunan daerah, melainkan masih diperlakukan sebagai agenda tambahan, kebijakan tambahan yang muncul sesekali ketika momentum politik memungkinkan.
Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan inklusif di NTB adalah minimnya koordinasi lintas sektor. Pendidikan inklusif bergerak sendiri, layanan sosial berjalan sendiri, dan kebijakan ketenagakerjaan tidak sepenuhnya mengacu pada kerangka akomodasi yang wajar. Hal ini menciptakan fragmentasi kebijakan, suatu kondisi yang sering kali membuat penyandang disabilitas tidak memperoleh layanan secara utuh.
Misalnya, banyak sekolah yang menyatakan siap menerima murid penyandang disabilitas, namun tidak memiliki guru pendamping khusus, fasilitas adaptif, maupun sistem asesmen yang tepat. Sementara di sektor ketenagakerjaan, peluang kerja untuk difabel masih sebatas program CSR, belum masuk ke dalam kebijakan ketenagakerjaan daerah yang bersifat mengikat.
Dengan demikian, perayaan inklusi setiap tahun hanya mempertegas paradoks: semakin kerasnya seruan inklusi yang disampaikan di panggung, semakin terlihat jarak antara idealitas dan praksis kebijakan.
Di tengah-tengah implementasi kebijakan daerah, komunitas dan organisasi berbasis masyarakat, seperti SHG (Self-Help Group), jaringan advokasi, dan rumah singgah, menjadi aktor yang benar-benar menghadirkan perubahan. Mereka bergerak dalam logika yang berbeda dari birokrasi. Bagi komunitas, inklusi bukan seremonial, melainkan kebutuhan hidup sehari-hari.
Pelatihan ekonomi inklusif, pendampingan orang tua, penyediaan rumah singgah, dan advokasi pendidikan menjadi bentuk-bentuk perubahan mikro yang justru menghasilkan dampak nyata. Dalam perspektif studi pembangunan, inilah bagian dari inovasi sosial inovasi berbasis komunitas yang hadir karena negara belum menjalankan fungsinya secara maksimal.
Dengan kata lain, difabel di NTB bukan menunggu perubahan, tetapi membangunnya sendiri, meski sering kali dengan sumber daya yang terbatas.
Jika NTB ingin benar-benar menjadi provinsi inklusif, maka perubahan harus bergerak dari seremonial ke struktural. Pemerintah daerah perlu memastikan Penganggaran inklusif (penganggaran inklusif) yang mengintegrasikan penyandang disabilitas ke setiap sektor, Penguatan kapasitas energi layanan, baik guru, tenaga kesehatan, maupun aparat desa, Pemantauan dan evaluasi kebijakan yang melibatkan difabel sebagai subjek, bukan objek, Desain kebijakan berbasis data, bukan sekedar agenda politik lima tahunan, Strategi kemitraan dengan komunitas, bukan hanya menghadirkan mereka sebagai peserta acara.
Perubahan tidak lahir dari peristiwa peringatan, tetapi dari keberanian pemerintah untuk menghadapi masalah struktural secara berkelanjutan.
Inklusi Bukan Panggung, Melainkan Proses Panjang
“Jejak: Disabilitas Membangun NTB” bukan sekadar slogan, tetapi cermin bahwa transformasi sejati muncul dari ruang paling sunyi, dari komunitas yang bekerja tanpa spanduk, dari ibu-ibu yang mengantarkan anaknya ke sekolah inklusi yang belum sempurna, dari kelompok difabel yang berjuang membuka peluang kerja, dan dari organisasi kecil yang tetap bertahan di tengah terbatasnya.
Jika pemerintah ingin selaras dengan semangat itu, maka HDI bukan lagi momen euforia seremonial, melainkan titik refleksi untuk menata ulang arah kebijakan. Karena inklusi hanya akan bermakna jika jejak perubahan tidak berhenti di panggung, tetapi sampai ke rumah-rumah warga penyandang disabilitas yang selama ini menantikan kehadirannya.